Opini
Bawang Merah dan Bawang Putih: Koperasi Merah Putih
Tak sedikit program ekonomi rakyat berhenti di pintu birokrasi desa, bukan karena ide buruk, tetapi tak lolos dari filter kuasa tak tertulis.
DALAM kisah klasik “Bawang Merah dan Bawang Putih”, kita diajarkan bahwa kebaikan yang tulus sering kali tersingkir oleh kelicikan yang berwajah manis.
Zaman berganti, teknologi melesat, jargon pembangunan terus diperbarui, namun pola kisah itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wujud dimulai dari rumah kayu dan tungku api, menjadi ruang rapat dan dokumen kebijakan.
Kini, dongeng lama itu menemukan panggung barunya di dunia ekonomi rakyat: Koperasi Merah Putih.
Program ini hadir dengan gegap gempita dan narasi kebangsaan yang menggugah: menyatukan kekuatan ekonomi desa, memperkuat koperasi rakyat, dan meneguhkan semangat gotong royong dalam wajah modern.
Dalam semangatnya, kita seperti disuguhi mimpi besar tentang kemandirian ekonomi Indonesia dari akar rumput. Namun seperti halnya banyak mimpi di negeri ini, aroma kepentingan sering lebih tajam tercium daripada harumnya niat baik.
Ketika modal yang diklaim mencapai ratusan triliun diumumkan, publik sempat terpana. Tetapi bagi kalangan ekonomi, angka itu lebih mirip dongeng baru ketimbang rencana bisnis yang masuk akal.
Klaim keuntungan hingga Rp 2000 triliun per tahun terdengar megah, namun kosong dari logika. Transparansi data dan kejelasan sumber dana menjadi persoalan sejak awal.
Apa yang seharusnya dimulai dengan kepercayaan publik justru menimbulkan tanda tanya: apakah Koperasi Merah Putih benar-benar dirancang untuk rakyat, atau sekadar proyek politik yang diselimuti simbol nasionalisme?
Ironisnya, koperasi yang mengusung nama “merah putih” justru mulai dipertanyakan kemerahan niat dan putihnya nurani para pengelolanya.
Masalah terbesar program semacam ini bukan terletak di gedung kementerian atau meja menteri, tetapi di lapangan atau di desa, di mana struktur sosial sudah lama berakar dan sering kali lebih kuat daripada peraturan.
Dalam dunia nyata pembangunan desa, selalu ada “penjaga gerbang tak bernama” dengan sosok-sosok yang tidak tercatat dalam struktur formal, tetapi semua pihak tahu betapa besar pengaruhnya.
Mereka adalah mereka yang kerap memperlakukan mandat sebagai mahkota dan akses sebagai alat kuasa.
Mereka memposisikan diri sebagai pengatur lalu lintas pembangunan: siapa yang boleh lewat, siapa yang harus menunggu, siapa yang tak pantas melintas.
Di tangan mereka, program pembangunan berubah menjadi semacam ritual: sebelum memulai, harus menghadap, memberi salam, dan menunggu restu.
Kita mengenal mereka bukan dari kartu identitas, tetapi dari gaya bicara dan sorot mata. Mereka hadir di setiap rapat koordinasi, duduk di kursi tengah, berbicara paling banyak, dan paling keras menegaskan bahwa semua harus “terkoordinasi melalui mereka”.
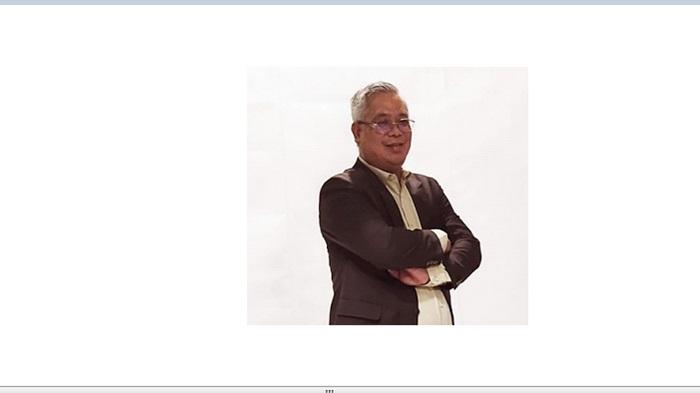



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.