Opini
Tatkala Banjir dan Kekeringan Tiba Bersamaan
Sumsel jadi potret kontras: wilayah rawa di timur seperti Banyuasin rawan banjir, sedangkan wilayah barat seperti OKU rentan kekeringan.
Dr. M.H.Thamrin
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya)
Ringkasan Berita:
- Bencana hidrometeorologi (banjir & kekeringan) ekstrem di Sumsel akibat perubahan iklim meningkat, akibat kegagalan tata kelola.
- Koordinasi antar-dinas lemah, data terputus, dan kurangnya partisipasi/komunikasi warga melipatgandakan dampak bencana.
- Perlu Kolaborasi (Collaborative Governance) antara pemerintah-warga, transparansi informasi, dan pembelajaran kebijakan berkelanjutan.
SRIPOKU.COM - Beberapa bulan terakhir, cuaca di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan wajah yang kian ekstrem.
Di satu wilayah, hujan turun berhari-hari tanpa henti, menenggelamkan jalan dan menahan aktivitas warga. Di wilayah lain, tanah mulai retak dan sumur-sumur mengering. Air berlebih di satu sisi, kekeringan di sisi lain—sebuah ironi yang kini menjadi keseharian di banyak daerah.
Bagi warga, ini bukan lagi anomali cuaca, melainkan persoalan hidup sehari-hari. Petani bingung menentukan pola tanam, nelayan kehilangan kepastian air pasang, dan warga kota gelisah setiap kali hujan deras turun lebih dari dua jam.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola iklim kita masih tertinggal dari perubahan alam yang semakin ekstrem (BMKG, 2025).
Dari Alam ke Tata Kelola
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan curah hujan ekstrem di Indonesia meningkat lebih dari 20 persen dalam dua dekade terakhir, sementara periode kering makin panjang (BMKG, 2025).
BNPB mencatat, lebih dari 98 persen bencana di Indonesia tahun lalu bersumber dari faktor hidrometeorologi—banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan (BNPB, 2024).
Namun, kesiapan institusi kita belum seimbang dengan ancaman tersebut. Koordinasi antara dinas pertanian, lingkungan, dan perumahan masih sering tumpang tindih.
Infrastruktur fisik seperti tanggul dan pompa air memang penting, tapi tak akan cukup tanpa tata kelola yang lentur dan terintegrasi (World Bank, 2023).
Dalam banyak kasus, kegagalan bukan karena kurang proyek, melainkan karena data tak terhubung, koordinasi lemah, dan akuntabilitas belum berjalan.
Sumsel menjadi potret kontras: wilayah rawa di timur seperti Banyuasin rawan banjir, sedangkan wilayah barat seperti OKU dan Muba rentan kekeringan dan kebakaran lahan.
Dua ekstrem ini menuntut pendekatan berbeda tapi saling terkait dalam pengelolaan air dan ruang. Program rehabilitasi lahan gambut dan irigasi sebenarnya sudah berjalan, namun pelaksanaannya masih dominan proyek fisik. Padahal, keberhasilan adaptasi iklim bergantung pada cara masyarakat dilibatkan.
Ketika kelompok tani diberi ruang untuk mengelola embung dan kanal lokal, hasilnya jauh lebih efektif dibanding proyek top-down (FAO, 2023).
Di Palembang sendiri, banjir perkotaan lebih sering disebabkan oleh drainase tersumbat dan sampah rumah tangga.
Pemerintah kota rutin mengeruk saluran, tapi tanpa partisipasi warga, air tetap mencari jalannya sendiri.
Perubahan iklim membuat curah hujan sulit diprediksi, tetapi buruknya tata ruang dan perilaku sosial membuat dampaknya berlipat ganda.
Komunikasi sebagai bagian dari Tata Kelola
Adaptasi iklim bukan hanya soal kebijakan, tapi juga komunikasi. Saat pemerintah mengumumkan “status siaga bencana”, banyak warga tak tahu apa arti praktisnya. Ke mana harus melapor, bagaimana melindungi aset, atau siapa yang bisa dihubungi? Padahal, komunikasi publik yang jelas bisa menyelamatkan banyak nyawa.
Di beberapa daerah, inovasi kecil mulai muncul. Sejumlah desa di Ogan Ilir, misalnya, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis pesan singkat dan radio komunitas.
Informasi debit sungai dan prakiraan cuaca disebar langsung oleh perangkat desa. Langkah sederhana ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tepat bisa menjadi bagian penting dari tata kelola kebencanaan yang efektif.
Sebagai orang yang belajar kebijakan publik, saya percaya bahwa governance dan communication harus berjalan seiring.
Pemerintah perlu membangun sistem informasi risiko yang terbuka, sehingga warga tahu apa yang sedang terjadi di sekitar mereka.
Peta rawan banjir, lokasi aman, dan jalur evakuasi seharusnya mudah diakses, bukan tersimpan di laporan teknis.
Mencari Model Tata Kelola Baru
Banjir dan kekeringan yang datang bergantian seolah sedang menguji bukan hanya daya tahan kita terhadap alam, tetapi juga cara kita mengatur kehidupan bersama.
Dalam pandangan Anthony Giddens (1984), hubungan antara negara dan warga selalu bersifat timbal balik: struktur kebijakan membentuk perilaku masyarakat, namun masyarakat pun membentuk kembali struktur itu lewat tindakan sehari-hari.
Maka, keberhasilan kebijakan iklim tidak hanya bergantung pada rancangan di atas kertas, tetapi pada bagaimana nilai dan perilaku publik ikut menghidupinya.
Dari sinilah pentingnya membangun tata kelola yang mendengar sebelum mengatur.
Banyak hal sederhana bisa menjadi pintu masuknya: musyawarah desa yang membahas peta risiko banjir, gotong royong menjaga kanal dan embung, atau kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah dalam memantau data curah hujan.
Inilah semangat collaborative governance (Ansell & Gash, 2008) dalam bentuk paling nyata—kolaborasi yang lahir dari kebutuhan, bukan dari undangan resmi.
Lebih jauh, kebijakan publik yang baik tidak semata-mata mengejar efisiensi, melainkan berupaya membangun kepercayaan.
Public value (Moore, 1995) tumbuh ketika warga merasa dilibatkan dan pemerintah tampil transparan serta konsisten.
Dalam konteks Sumatera Selatan, nilai publik bisa berarti saluran air yang bersih karena warga dan pemerintah bekerja bersama, atau kejelasan informasi ketika status siaga bencana diumumkan. Hal-hal kecil seperti itu membentuk rasa percaya, yang menjadi fondasi bagi kebijakan apa pun.
Dan tentu, tak ada kebijakan yang sempurna pada percobaan pertama. Setiap banjir, setiap kekeringan, semestinya menjadi ruang belajar bersama.
Dalam literatur kebijakan publik mutakhir, policy learning dipahami bukan sekadar evaluasi pascabencana, tetapi proses reflektif dan partisipatif yang terus memperkaya kapasitas institusi dan masyarakat untuk beradaptasi (Dunlop & Radaelli, 2018; Mukhtarov et al., 2023).
Jika semua ini berjalan—kolaborasi yang tulus, nilai publik yang hidup, dan kebiasaan belajar yang berkelanjutan—maka kita akan memiliki tata kelola yang bukan sekadar kuat, tapi juga lentur dan manusiawi. Karena pada akhirnya, mengelola bencana dan perubahan iklim bukan sekadar urusan teknis, melainkan cara kita membangun hubungan saling percaya di antara warga dan negara.
Sumatera Selatan mengajarkan kita bahwa menghadapi krisis iklim bukan soal menunggu bantuan, tetapi soal mengelola solidaritas.
Banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan adalah ujian bagi cara kita bernegara.
Bila pemerintah mampu mendengar dan masyarakat mau terlibat, maka bencana bisa berubah menjadi pelajaran, dan air—baik yang berlebih maupun yang hilang—kembali menjadi sumber kehidupan, bukan sumber kecemasan. (*)
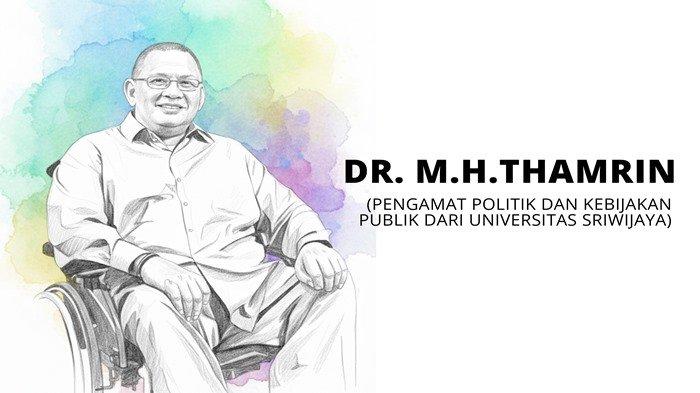














![[FULL] Roy Suryo Berlindung di Balik Penelitian, Pakar: Kalau Malah Menyerang Personal Tetap Pidana](https://img.youtube.com/vi/8fzdVBIhfxw/mqdefault.jpg)





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.