Opini
Suara yang Hilang, Demokrasi yang Tergerus
Demokrasi baru akan tegak bila suara rakyat, sekecil apa pun, tidak dibiarkan menguap sia-sia.
Oleh: Dr. M.H.Thamrin
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya)
SRIPOKU.COM - Beberapa waktu lalu seorang tetangga bercerita setelah pemilu. Dengan nada kecewa ia berkata, “Saya sudah memilih, tapi rasanya percuma saja. Calon yang saya pilih tidak pernah lolos.”
Kalimat sederhana itu menyentil saya. Bagaimana mungkin seorang warga yang sudah berpartisipasi justru merasa suaranya tak bermakna? Kenyataannya, perasaan itu bukan keliru.
Dalam setiap pemilu, selalu ada suara yang sah namun tak pernah sampai ke kursi parlemen. Ia hilang di sepanjang proses konversi suara menjadi kursi.
Fenomena inilah yang dalam tulisan ini saya sebut sebagai suara yang hilang. Suara yang hilang berbeda dari golput atau suara tidak sah. Ia justru lahir dari partisipasi aktif. Dalam literatur politik, fenomena ini kerap disebut dengan dua istilah: wasted votes dan unrepresented votes.
Istilah wasted votes digunakan dalam konteks sistem distrik tunggal seperti Amerika Serikat atau Inggris.
Douglas Rae (1967), dalam buku klasik The Political Consequences of Electoral Laws, menyebut suara terbuang sebagai suara yang diberikan kepada kandidat yang kalah atau suara tambahan yang tidak lagi memengaruhi hasil.
Belakangan, konsep ini dipakai pula untuk mengukur praktik gerrymandering melalui apa yang dikenal sebagai efficiency gap (Stephanopoulos & McGhee, 2015).
Semakin besar jumlah suara terbuang, semakin terlihat manipulasi pembagian distrik untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu, unrepresented votes lebih lazim dalam sistem proporsional, seperti di Indonesia. Suara disebut tidak terwakili ketika, meski sah, tidak menghasilkan kursi karena aturan kelembagaan.
Ambang batas parlemen menjadi contoh paling jelas. Pada Pemilu 2019, data KPU mencatat sekitar 13,8 juta suara—hampir 12 persen suara sah—tidak pernah sampai ke Senayan karena partai-partai pengusungnya gagal melewati parliamentary threshold 4 persen.
Jumlah sebesar ini setara dengan populasi sebuah provinsi, tetapi tidak satu pun kursi lahir darinya (Siregar, 2020).
Dua istilah ini menunjukkan sisi yang berbeda. Wasted votes menekankan inefisiensi kompetisi, sedangkan unrepresented votes menyoroti eksklusi kelembagaan.
Bedanya halus, tetapi penting. Yang satu akibat sifat kompetisi elektoral, yang lain akibat desain aturan pemilu.
Mengapa suara bisa hilang?
Ada beberapa penyebab utama. Pertama, desain sistem pemilu itu sendiri. Sistem distrik tunggal hanya menyisakan satu pemenang di setiap daerah, membuat sebagian besar suara otomatis terbuang.
Sistem proporsional memang lebih representatif, tetapi tetap melahirkan suara hilang karena ambang batas, formula konversi suara ke kursi, hingga ketidakseimbangan alokasi kursi antar-daerah (malapportionment).
Kedua, fragmentasi partai politik. Semakin banyak partai kecil, semakin besar pula potensi suara tersebar tipis dan akhirnya tak terkonsolidasi, lalu terbuang karena partai gagal memenuhi syarat minimal.
Ketiga, tata kelola pemilu yang tidak adaptif. Pippa Norris (2014), melalui Electoral Integrity Project, menegaskan bahwa integritas pemilu adalah fondasi demokrasi.
Pemilu bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tetapi apakah setiap suara diperlakukan adil dan punya peluang setara untuk dihitung.
Bila jutaan suara hilang karena aturan, itu bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan keretakan pada akar demokrasi.
Pandangan serupa disampaikan Luis E. M. Torres (2015), yang menekankan bahwa aturan pemilu—mulai dari alokasi kursi, distribusi distrik, hingga ambang batas—bisa memperkuat atau justru melemahkan legitimasi.
Bila aturan gagal menjamin keterwakilan, yang runtuh adalah kepercayaan publik pada sistem politik itu sendiri.
Fenomena suara yang hilang membawa implikasi serius. Ia menimbulkan defisit representasi: jutaan pemilih merasa suaranya tak bermakna meski sudah berpartisipasi.
Ia menciptakan bias representasi karena partai besar semakin dominan, sementara partai kecil dan pemilihnya tersisih.
Ia bisa menggerogoti legitimasi parlemen, karena publik mempertanyakan seberapa sah wakil rakyat itu benar-benar mewakili. Dan pada akhirnya, ia bisa melahirkan apatisme: pemilih yang berulang kali melihat suaranya hilang mungkin memilih untuk tidak datang lagi ke bilik suara.
Mencari Jalan Keluar
Pertanyaannya: apakah suara yang hilang bisa dihapuskan? Hampir mustahil.
Setiap sistem pemilu pasti menyisakan sebagian suara yang tidak menghasilkan kursi. Namun, kita bisa dan seharusnya meminimalkan jumlahnya. Ambang batas parlemen, misalnya, layak dikaji ulang.
Apakah threshold 4 persen masih relevan untuk konteks multipartai Indonesia, atau justru membuat jutaan suara sah terbuang?
Alternatif lain adalah memperbaiki formula konversi suara agar lebih proporsional, serta memperkuat pendidikan politik pemilih agar pilihan mereka lebih strategis.
Beberapa riset terbaru bahkan mengusulkan redistribusi suara hilang atau mekanisme transferable votes untuk mengurangi dampak eksklusi (Aragonés et al., 2025).
Arend Lijphart (1999) pernah menegaskan bahwa sistem pemilu adalah jantung demokrasi. Dari sinilah denyut kehidupan politik ditentukan.
Jika sistem ini terlalu banyak membuang suara, maka yang hilang bukan sekadar kursi, tetapi legitimasi demokrasi itu sendiri.
Pandangan Lijphart kini mendapat gema dari pemikir kontemporer seperti Norris maupun Torres: demokrasi hanya sehat bila suara rakyat benar-benar dihitung.
Bagi saya, pembicaraan tentang suara yang hilang bukan soal hitung-hitungan teknis semata. Ia menyangkut rasa keadilan politik warga.
Demokrasi baru akan tegak bila suara rakyat, sekecil apa pun, tidak dibiarkan menguap sia-sia.
Karena itu, setiap kali kita membicarakan pemilu, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya siapa yang akan menang, melainkan seberapa banyak suara yang akan hilang—dan apa yang bisa kita lakukan agar jumlahnya semakin kecil. (*)
| Peringatan Dini: IPM Kota Palembang Sangat Tinggi Tapi Tersendat |

|
|---|
| Cerdas Finansial, Aman dari Penipuan: Pentingnya Literasi Keuangan di Era Digital |

|
|---|
| Teror Likuiditas Dana Rp 200 Triliun: “Offside”? |

|
|---|
| Serapan Anggaran MBG Rendah: Diduga Ada Skandal 'Uang Titik' Dapur Rp 50 Juta di Palembang |

|
|---|
| Refleksi Hari Statistik Nasional |

|
|---|










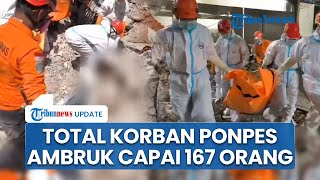





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.