Opini
Membedah Label Negatif Generasi Z, Manja dan Mudah Tertekan
Berdasarkan hasil SP 2020 jumlah Generasi Z di Indonesia cukup dominan diperkirakan sebesar 27,94 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
GENERASI Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997-2012. Saat ini perkiraan usia Generasi Z antara 13 – 28 tahun. Diduga Generasi Z sudah banyak yang berpendidikan tinggi baik tamatan Strata 2 (S-2) maupun Strata 3 (S-3).
Berdasarkan hasil SP 2020 jumlah Generasi Z di Indonesia cukup dominan diperkirakan sebesar 27,94 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 74,93 juta jiwa di tahun 2020.
Dalam kehidupan sehari-hari atau seminggu terakhir ini, coba jujur kita akui seberapa sering anda mendengar keluhan tentang Generasi Z di berbagai tempat. Di ruang rapat? Di warung kopi? Bahkan di grup WhatsApp? Kita mungkin sering mendengar narasi yang relatif sama secara berulang yang diucapkan mengenai Generasi Z.
Mereka dibilang generasi stroberi, manja, dan mudah tertekan. Di dunia kerja, mereka dicap punya mental tempe, dianggap rapuh, banyak menuntut, dan maunya serba instan. Mereka juga dituding sebagai kutu loncat yang tidak loyal dan kecanduan gawai yang membuat mereka dianggap antisosial.
Label-label ini selalu diulang hingga nyaris menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Kita sering mengangguk-angguk setuju, merasa prihatin dengan masa depan yang akan dipegang generasi yang katanya rapuh.
Bagaimana jika saya katakan bahwa semua label itu bukan hanya keliru, tetapi merupakan sebuah bentuk kemalasan intelektual kita sebagai penilai? Bagaimana jika di balik setiap stereotip yang dilekatkan pada Generasi Z, ternyata ada sebuah kekuatan, sebuah adaptasi cerdas terhadap dunia yang diwariskan generasi-generasi sebelumnya kepada mereka? Mungkin sudah saatnya kita berhenti mengeluhkan dan mulai mendengarkan mereka.
Membedah Label
Harus diakui banyak label negatif yang telah disematkan bagi Generasi Z dikehidupannya sehari-hari. Agar kesalahan memahami Generasi Z tidak semakin dalam, mari kita bedah satu per satu label-label yang disematkan kepada Generasi Z, yaitu:
Pertama, mitos generasi manja yang selalu bicara soal kesehatan mental dan work-life balance. Benarkah mereka cengeng dan manja? Atau, mungkinkah mereka adalah generasi pertama yang cukup bijak untuk tidak mengulang kesalahan generasi sebelumnya?
Mereka telah melihat bagaimana generasi orang tua dan kakaknya Generasi Milenial tumbang karena burnout, terjebak dalam budaya kerja toksik yang mengagungkan jam kerja panjang sebagai lencana kehormatan.
Tuntutan mereka akan fleksibilitas, keseimbangan hidup, dan perhatian pada kesejahteraan mental bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah sebuah strategi bertahan hidup yang pragmatis.
Mereka secara fundamental mendefinisikan ulang arti produktivitas, bukan lagi tentang berapa lama bokong menempel di kursi kantor, melainkan tentang dampak dan hasil yang nyata.
Mereka paham bahwa tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset utama untuk bisa berkarya secara berkelanjutan. Bukankah ini sebuah kecerdasan, bukan kerapuhan.
Kedua, tuduhan pemalas dan serba instan. Ketidaksabaran mereka terhadap proses birokrasi yang lamban sering disalahartikan sebagai kemalasan. Padahal, ini adalah cerminan dari efisiensi.
Sebagai makhluk digital sejati, mereka tumbuh di dunia di mana informasi dan solusi hanya sejauh satu klik. Mereka terbiasa mencari cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah.
Ketika dihadapkan pada sistem kerja yang kuno dan tidak efisien, tentu saja mereka frustrasi. Ketidaksabaran mereka bukanlah dosa, melainkan katalisator untuk inovasi. Mereka mendorong kita semua untuk mengadopsi teknologi dan proses kerja yang lebih cerdas dan lebih cepat.
Ketiga, stereotip antisosial dan kecanduan gawai. Memang benar, interaksi mereka sering kali termediasi oleh layar. Namun, menganggap ini sebagai tanda antisosial adalah sebuah kesalahpahaman besar.
Komunitas mereka hanya berbeda bentuk, tidak lagi dibatasi oleh geografi, melainkan oleh minat dan nilai yang sama di dunia digital.
Mereka adalah The Communaholic, generasi yang lihai memanfaatkan konektivitas untuk kebaikan sosial. Anda pasti pernah melihat fenomena Twitter, please do your magic.
Dengan satu unggahan, mereka bisa memobilisasi bantuan untuk pedagang kecil yang kesulitan atau menggalang donasi untuk korban bencana dalam hitungan jam.
Mereka mengubah scrolling pasif menjadi partisipasi sipil yang aktif. Konektivitas digital di tangan mereka bukanlah pelarian dari dunia nyata, melainkan alat untuk memperbaikinya.
Keempat, loyalitas cap kutu loncat. Cap kutu loncat adalah yang paling sering kita dengar yang menggambarkan seolah-olah Generasi Z memiliki loyalitas rendah.
Tetapi coba kita balik logikanya. Apakah masalahnya ada pada mereka, atau pada perusahaan/institusi yang gagal memberikan alasan bagi mereka untuk tinggal? Loyalitas Generasi Z tidak lagi buta. Mereka tidak akan mengabdi seumur hidup pada satu tempat hanya karena tradisi.
Baca juga: Sosok Akmal Riansyah, Pemuda Baik dan Taat Beribadah, Jadi Panutan Remaja Setempat
Loyalitas mereka bersifat transaksional berbasis nilai. Mereka akan memberikan seluruh energi dan kreativitasnya selama pekerjaan itu memberikan tiga hal, yaitu: pertumbuhan (kesempatan belajar dan mengembangkan diri), tujuan (purpose yang sejalan dengan nilai pribadi mereka), dan penghargaan (bukan hanya gaji, tapi juga fleksibilitas dan pengakuan).
Ketika salah satu dari tiga hal ini hilang, mereka akan mencari misi berikutnya. Ini bukan ketidakloyalan, ini adalah arsitektur karier yang cerdas untuk dunia yang terus berubah. Mereka menantang perusahaan untuk terus menjadi lebih baik.
Di balik semua itu, ada satu benang merah yang menyatukan karakter generasi ini yakni optimisme yang pragmatis. Mereka sangat sadar akan masalah dunia (krisis iklim, ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan sosial). Tingkat kecemasan mereka memang dilaporkan tinggi. Namun, mereka tidak lumpuh oleh pesimisme.
Kecemasan itu justru mendorong mereka untuk bertindak secara praktis. Dari hasil riset IDN Research Institute bersama Populix yang berjudul Indonesia Gen Z Report 2022, siapa sangka di tengah citra konsumtif, prioritas utama hidup mereka adalah membahagiakan orang tua (83 persen) dan menabung untuk masa depan (81 persen).
Mereka adalah kelompok demografis yang mendominasi porsi investor ritel di pasar modal Indonesia. Ini bukan perilaku generasi yang hanya memikirkan kepuasan sesaat. Ini adalah langkah-langkah nyata dari generasi yang tahu bahwa mereka harus membangun jaring pengaman mereka sendiri. Hal itu mengungkapkan bahwa Generasi Z bukanlah masalah yang harus kita selesaikan.
Mereka adalah cerminan dari masa depan yang sudah ada di depan mata. Mereka adalah alarm pengingat bagi kita semua untuk beradaptasi. Cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, cara sebuah mereka membangun kepercayaan, semuanya sedang mereka desain ulang.
Penutup
Di tahun Indonesia Emas 2045 perkiraan usia Generasi Z antara 33 - 48 tahun. Di saat itu sebagian besar dari mereka diperkirakan rata-rata sudah mencapai puncak karir, aktor utama pembangunan, dan pemegang kunci pengambil kebijakan.
Melihat begitu besarnya peranan dan kedudukan Generasi Z baik menjelang Indonesia Emas 2045, pada Indonesia Emas 2045, maupun di masa setelah Indonesia Emas 2045, apakah kita masih terus-menerus melabeli mereka dengan stereotip using dan mengeluhkan betapa berbedanya mereka.
Atau apakah kita sejak dini sudah melihat keunggulan tersembunyi mereka dibalik banyaknya label negatif yang ditempelkan, apakah kita sudah memahami kekuatan di balik apa yang kita anggap sebagai kelemahan, dan mulai berkolaborasi dengan para arsitek masa depan ini. Jawaban dan pilihan ada di tangan kita. (*)
Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.















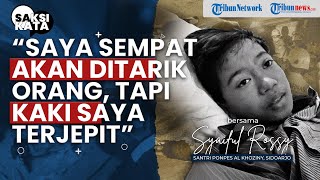





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.