Mimbar Jumat
Mengambil Hikmah Peringatan Isra’ Mikraj Bersama Masyarakat Bugis di Sungsang
Alam Sumatera Selatan terbentang seluas 91.592,43 km2 atau kurang lebih seluas negara Portugal, dan dihuni oleh 8.973.168 jiwa (Juni 2024).
Oleh: Dr. Muhammad Walidin, M.Hum.
Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Alam Sumatera Selatan terbentang seluas 91.592,43 km2 atau kurang lebih seluas negara Portugal, dan dihuni oleh 8.973.168 jiwa (Juni 2024).
Penduduk asli Sumatera Selatan dikenal dengan nama suku Melayu. Akan tetapi, banyak pula suku bangsa yang juga berdiam di Palembang sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu suku bangsa yang juga menjadi bagian dari penduduk Sumatera Selatan adalah suku (Melayu) Bugis yang mendiami bagian pesisir.
Pada dasarnya, suku Bugis adalah sebutan untuk penduduk yang mendiami bagian Selatan pulau Sulawesi dan terdiri dari empat suku besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sejak datangnya kolonial Belanda di nusantara pada kurun abad 17, sebagian orang Bugis melakukan migrasi dari tempat asalnya ke berbagai belahan bumi lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Singapore, Australia, bahkan Afrika Selatan (Sitti Rachmawati Yahya, 2013).
Lineton, J (1975) dalam tulisannya Bugis Migrants and Wanderers mencatat bahwa sebagai pelaut ulung, suku ini telah banyak mendiami berbagai benua dan membentuk komunitas di sana dengan sebutan Bugis Village.
Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemukiman Masyarakat Bugis di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Banyasin, termasuk daerah Sungsang.
Dalam perjalanan monitoring KKN UIN Raden Fatah ke 82 ke Sungsang di awal bulan Rajab 1446 Hijriyah/Januari 2025, saya menghadiri undangan sebuah perayaan/pengajian Isra’ Mikraj yang diadakan di rumah salah satu tokoh di desa tersebut.
Perayaan ini saya sebut sebagai kegiatan yang Istimewa, terutama karena format pengajian keislamannya lebih intens/dalam sehingga meninggalkan dampak yang lebih dalam juga bagi para pendengarnya.
Sebagai Gambaran umum, pengajian Isra Mikraj ini diadakan di rumah Masyarakat dan bisa berulang dalam satu periode bulan Rajab.
Selain sebagai ajang silaturrahmi antar sesama warga, perayaan ini juga menebalkan keimanan anggota masyarakat terhadap syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan penegakan ibadah salat.
Peringatan ini biasa dilakukan oleh Masyarakat yang mengikuti ajaran Tarekat Khalwatiyah; sebuah varian sufisme yang lahir di Asia Tengah pada abad 15 M.
Secara Bahasa, ‘Isra‘ berarti ‘Memperjalankan‘ dalam bentuk verba transitif. Dalam konteks peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah SWT dari Masjid al-Haram di Mekah ke Masjid al-Aqsa di Yerusalem dalam satu malam (Tafsir Ibnu Kasir).
Sementara kata Mikraj berasal dari kata ‘araja‘ (naik/meninggi) dalam bentuk ism al-Alat (nama alat), yang berarti tangga atau alat untuk naik. Secara eksplisit, kata "Mikraj" tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
| Radikalisme Agama dan Pedagogy of Love |

|
|---|
| Menjaga Bumi: Warisan Peradaban Islam dalam Menghadapi Krisis Lingkungan |

|
|---|
| Toleransi dan Pendidikan Agama Islam, Menjaga Harmoni dalam Kehidupan Berbangsa |

|
|---|
| Serukan Aspirasi Tanpa Anarki Pesan Nabi untuk Penduduk Negeri |

|
|---|
| Refleksi Ruhani di Bulan Merdeka, Memaknai Kebebasan Jiwa saat Tidur |

|
|---|









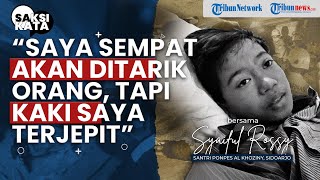





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.