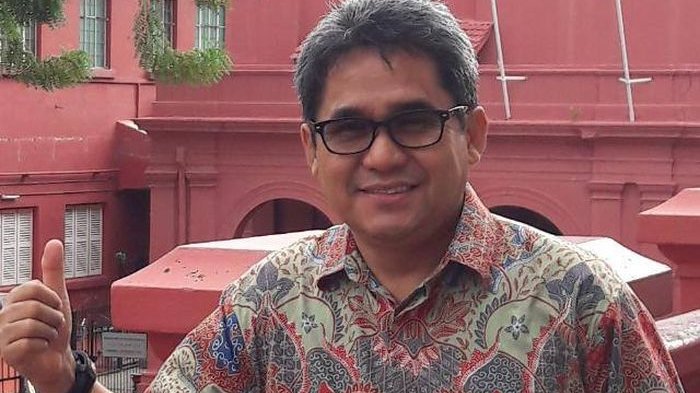Dialog Papua: Mencegah Konflik Berkepanjangan
Konflik dan kerusuhan di Papua seakan tidak pernah berhenti dan hingga kini belum ada solusi yang akurat.
Dialog Papua:
Mencegah Konflik Berkepanjangan
Oleh: Prof Abdullah Idi.
Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang
Konflik dan kerusuhan di Papua seakan tidak pernah berhenti dan hingga kini belum ada solusi yang akurat.
Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, konflik Papua seakan terus terjadi dan berulang.
Kalau beberapa kasus konflik lainnya pada masa lalu dapat diselesaikan seperti kasus konflik Maluku dan Aceh (pernah minta Merdeka) serta Timor-Timur (minta referendum dan sudah merdeka), beda halnya dengan konflik Papua yang seakan belum ada suatu pendekatan dan solusi yang akurat.
Terbukti, setiap rezim (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) kasus Papua terus terjadi.
Tulisan ini, menganalisis faktor apa saja sebagai ‘akar’ konflik di Papua dan perlunya pendekatan dialog sebagai upaya merangkul kembali orang Papua sebagai bagian dari warga negara bangsa (nation state) Indonesia.
Diagnosa persoalan konflik Papua memiliki beragam perspektif. Dari perspektif ilmu sosial dalam keijakan pembangunan di Papua, setidaknya perlu memperhatikan faktor internal dan internal.
Faktor internal, dapat dikatakan bahwa sebagai evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terutama kebijakan dalam konteks sosio-historis pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.
Dari studi yang pernah dilakukan LIPI (2011), menunjukkan bahwa setidaknya terdapat beberapa ‘akar’ konflik Papua dalam kontek bagian dari NKRI.
Pertama, persoalan sosio-historis dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, dimana orang pada umumnya Papua berpandangan bahwa proses integrasi ke Indonesia belumlah benar.
Kedua, bertalian dengan operasi militer bertalian dengan konflik itu yang dipandang tidak terselesaikan.
Operasi militer pada Orde Lama (1965) hingga kini, orang Papua pada umumnya berpandangan sebagai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Karena adanya persepsi terhadap operasi militer yang demikian, telah menyebabkan tersosialisasi secara massif di kalangan masyarakat Papua, dimanapun berada, di Papua, di Jawa, dan bahkan di luar negeri.
Terlebih, dengan adanya media sosial, menunjukkan semakin lebih mudah tersosialisasi pandangan tersebut, seperti kasus Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
Tentu kasus Surabaya secara gradual akan semakin memperkuat solidaritas antarmereka sebagai bangsa Papua dan juga memunculkan simpatik ‘pihak luar’ yang sangat mungkin memang memiliki beragam kepentingan (vested interest).
Ketiga, pada sebagian besar anak muda Papua tampakterlihat radikal sebetulnya bisa juga adanya persepsi negatif terhadap masa lalu terhadap kekerasan militer dan persoalan HAM di Papua yang dipandang belum ada solusi substantif sebagai mana mestinya dimana militer me rasa aman terhadap masyarakat Papua.
Keempat, akumulasi dari ketiga persoalan diatas sebagai penyebab utama atas ‘akar’ konflik di Papua, telah memunculkan stigma di tengah masyarakat Papua, bahwa mereka merupakan masyarakat ‘kelas dua’ yang termarjinalkan.
Hal ini juga dapat diperkuat pula dengan kebijakan migrasi dan pembangunan dimana mereka merasa kurang dilibatkan atau terabaikan.
Akibatnya sentimen negatif terhadap migran pendatang tidak dapat dihindari, seperti terlihat amuk massa yang tidak jarang menyasar kepada etnistertentu yang non-Papua beserta aset-asetnya.
Hal ini bisa berpotensi munculnya masalah baru, berupa potensi konflik horizontal.
Dari beberapa ‘akar’ konflik yang bersifat internal diatas, agaknya mendorongnegara untuk ‘hadir’ dalam upaya resolusikonflik di Papua dengan merujuk kepada faktor-faktor utama (core of conflicts) sebagai ‘akar’ konflik di Papua.
Resolusi konflik di Papua tentunya memerlukan telaah mendalam terhadap ‘akar’ konflik tersebut sebagai konsideran kebijakan-kebijakan yang menyentuh kepada kebutuhan sosial (social needs) masyarakat Papua.
Cara pemerintah menyelesaikan kasus GAM-Aceh dan RMS-Maluku tentu patut diapresiasi dan dijadikan sebagai perbandingan dalam menuju resolusi.
Selain itu, faktor eksternal tidak kalah pentingnya menjadi analisis sebagai suatu‘akar’ konflik di Papua yang berkepanjangan.
Hal ini dapat dilihat bagaimana besarnya pengaruh bangsa asing terhadap Papua. Pada 1965, di era Orde lama, misalnya intervensibangsa Belanda terhadap Papua (Irian Jaya) yang seakan dengan terus berperan dalam konflik menciptakan dan menjaga konflik di Papua. Bendera Bintang Kejora disinyalir merupakan ciptaan bangsa Belanda dimana setiap ada konflik selalu dikibarkan sebagai simbol perjuangan tuntutan kemerdekaan.
Sama halnya dengan perjuangan separatismRepublik Maluku Selatan (RMS) pada masa lalu, dimana peran negeri Belanda juga begitu tampak setiap ada kerusuhan atau konflik di daerah tersebut.
Setidaknya setiap ada konflik sosial di daerah (Papua) tersebut, bendera Bintang Kejora pun selalu dikibarkan, meskipun barang kali bukanlah sebagai representatif aspirasi mayoritas orang Papua.
Selain itu semua, besarnya peran bangsa asing di Papua pada masa Orde Baru hingga Reformasi, dapat juga dilihat dari sejauhmana peran bangsa asing dalam mengelola dan ikut andil menikmati hasil sumber daya alam Papua.
Kehadiran PT. Freeport di Papua telah menjadikan Papua terkenal di dunia karena menghasilkan hasil tambang, terutama emas, yang menggiurkan dan diperebutkan bangsa asing, terutama investor Amerika.
Berbagai kebijakan bertalian kepemilikan saham pun terus dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia sehingga diharapkan memiliki mutual-benefit yang adil dan berimbang.
Akan tetapi, faktanya kini orang Papua dikatakan masih tertinggal dalam bidang kesejahteraan ekonomi padahal pemerintah telah melakukan Otonomi Khusus bagi Papua dan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mensejahterakan masyarakat Papua.
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No.4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).
UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.
Kalau begitu, suatu hal yang menjadi pertanyaan dan sekaligus perdebatan, sejauhmana bangsa Papua telah memperoleh manfaat dan kesejahteraan dari kehadiran dari beagam investor asing di Papua, termasuk dalam bidang perkebunan.
Begitu juga halnya, sejak ditetapkan Papua sebagai daerah Otonomi Khusus, sejauhmana terjadi perubahan sosial yang positip bagi masyarakat Papua.
Padahal dalam bidang politik, hampir semua kepala daerah (bupati dan gubernur) merupakan orang asli Papua.
Kalau berbagai kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan kehadiran parainvestor asing sudah membawa kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang kehidupan, tidak seharusnya adanya permintaan referendum untuk kemerdekaan.
Pemerintah juga sudah mengklaim sudah membangun berbagai infrastruktur di Papua tetapi sejauhmana sebetulnya (infrasruktur jalan) tersebut bermanfaat bagi masyarakat lokal, atau, apakah infrastruktur hanya akan memudahkan akses bagi investor asing tetapi sebaliknya bagi masyarakat lokal, hanya menimbulkan kecemburuan dan segregasi.
Tentunya sangat urgen menemukan beragam ‘akar’ masalah yang harus dicari secara detail dan spesifik sebagai upaya menuju resolusi konflik yang sesungguhnya dan permanen.
Secara struktural, jika posisi mayoritas masyarakat Papua sebagai penduduk asli (indigenous) tersubordinasi (subordinate) oleh kalangan pendatang (migran dan investor) dalam berbagai bidang kehidupan, konflik sosial akan mudah terjadi dan dapat berkepanjangan.
Sebaliknya, jika secara gradual dan pasti, posisi struktural masyarakat Papua berproses menjadi superordinasi (superordinate), konflik sosial diharapkan akan tereduksi secara gradual tapi pasti.
Faktanya, pembangunan bidang fisik yang dilakukan pemerintah agaknya tidak terlalu berkorelasi positip terhadap meredanya tensi konflik sosial di Papua, bahkan masih sering meminta adanyatuntutan referendum atau kemerdekaan.
Disinilah esensi perlunya dialog antara para tokoh asal Papua yang beragama latar belakang (tokoh adat,suku, agama, politisi, akademisi, pejabat, pengusaha) baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Hal ini bertujuan sebagai ikhtiar mencari ‘titik temu’ dan solusiterhadap beragam persoalan di Papua menuju solusi permanen.
Merawat dan mencegah konflik Papua yang berkepanjangan hanya dapat diselesaikanmelalui dialog antaraorang Papua dan Pemerintah RI itu sendiri.