Opini
Komunikasi Kebencanaan: Titik Buta Tata Kelola di Indonesia
Banyak pesan kebencanaan disusun dalam bahasa teknokratik yang sulit dipahami, padahal dalam situasi darurat, setiap detik dan setiap kata berarti.
Oleh: Dr. M.H. Thamrin
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya)
Ringkasan Berita:
- Komunikasi kebencanaan Indonesia adalah "titik buta". Saat bencana (98 persen hidrometeorologis) terjadi, kabar viral lebih cepat dari info resmi.
- Dibutuhkan paradigma baru: komunikasi bukan alat bantu, tapi bagian tata kelola. Informasi risiko harus jadi hak publik.
- Penting memperkuat jaringan partisipatif (misal, MPA di Karhutla) agar menjadi frontline communicators. Peran MPA harus diperluas: tak hanya memadamkan, tapi juga menyampaikan peringatan dini dan menjembatani warga.
SRIPOKU.COM - Setiap kali bencana datang, yang paling cepat menyebar bukan bantuan, melainkan kabar.
Begitu air naik di satu kabupaten, potongan video banjir segera memenuhi media sosial.
Warga saling mengirim pesan, tetapi informasi resmi baru muncul berjam-jam kemudian. Kepanikan sering lebih cepat dari koordinasi.
Fenomena ini berulang di banyak tempat—baik saat banjir di kota besar, kekeringan di pedesaan, maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan yang hampir saban tahun muncul di musim kering.
Semua memperlihatkan satu hal mendasar: bahwa komunikasi kebencanaan masih menjadi titik buta dalam tata kelola bencana di Indonesia.
Indonesia dikenal memiliki sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang paling kompleks di Asia Tenggara.
Kita memiliki BNPB di tingkat nasional, BPBD di setiap provinsi dan kabupaten, hingga berbagai dinas pendukung di sektor sosial, lingkungan, pertanian, Perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya. Juga TNI, Polri, Perusahaan, dan Komunitas.
Namun kompleksitas itu sering justru menjadi sumber lambatnya respons. Data BNPB (2024) menunjukkan, lebih dari 98 persen bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis—banjir, kekeringan, dan karhutla.
Di tengah ancaman yang terus meningkat, jalur koordinasi masih tersendat oleh tumpang tindih kewenangan dan komunikasi vertikal yang kaku.
Sumatera Selatan menjadi contoh klasik. Setiap musim kemarau, potensi karhutla sudah dapat diprediksi melalui data hotspot dari BMKG dan KLHK.
Namun koordinasi lintas instansi sering baru menguat setelah kabut asap menebal dan publik menyorot.
Informasi ada, tetapi tidak selalu sampai kepada pihak yang seharusnya bertindak lebih dulu.
Pemerintah daerah menunggu instruksi pusat, sementara masyarakat desa kebingungan menentukan langkah pencegahan. Kita punya regulasi yang detail, tetapi kehilangan kecepatan bertindak.
Makna Komunikasi Kebencanaan
Dalam tata kelola bencana, komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bagian dari proses pemerintahan itu sendiri.
Dalam konteks ini, istilah komunikasi kebencanaan—yang dalam literatur internasional disebut crisis and emergency risk communication (CERC)—merujuk pada pertukaran informasi yang cepat, jelas, dan empatik antara pemerintah, ahli, dan masyarakat untuk melindungi keselamatan publik (WHO, 2018; UNDRR, 2022).
Dengan demikian, komunikasi kebencanaan tidak boleh dipahami sempit sebagai strategi citra lembaga, tetapi sebagai mekanisme penyelamatan.
Namun di Indonesia, ia masih sering dipahami sempit sebagai urusan konferensi pers, bukan sistem informasi publik yang menyelamatkan nyawa.
Jika dicermati, akar persoalannya bukan hanya keterlambatan informasi, melainkan kurangnya empati dan kejelasan dalam komunikasi publik pemerintah.
Banyak pesan kebencanaan disusun dalam bahasa teknokratik yang sulit dipahami warga, padahal dalam situasi darurat, setiap detik dan setiap kata berarti.
Dalam collaborative governance (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015), tata kelola yang baik dibangun di atas kepercayaan dan kapasitas bersama.
Prinsip yang sama berlaku dalam komunikasi kebencanaan. Selama hubungan antarinstansi dibangun atas dasar formalitas, bukan kepercayaan, koordinasi akan tetap terjebak dalam birokrasi lambat.
Paradigma baru Komunikasi Kebencanaan
Kita membutuhkan paradigma baru: komunikasi sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar alat bantu kebijakan.
Informasi tentang risiko, peringatan, dan tindakan harus menjadi hak publik, bukan milik lembaga.
Langkah konkret dapat dimulai dari:
- Membangun platform komunikasi risiko terpadu di setiap provinsi yang menggabungkan data dari BMKG, BPBD, dan KLHK;
- Memperkuat kapasitas juru bicara daerah agar cepat, jelas, dan dipercaya;
- Melibatkan universitas serta media lokal sebagai mitra pengetahuan; dan
- Memperkuat jaringan partisipatif seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk di berbagai wilayah rawan karhutla.
Selama ini, MPA berperan penting dalam pencegahan dan pemadaman dini (KLHK, 2024).
Namun peran mereka dapat diperluas: tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menjadi simpul komunikasi publik — menyampaikan peringatan dini, melaporkan kondisi lapangan, dan menjembatani warga dengan pemerintah.
Dengan pelatihan komunikasi risiko yang memadai, MPA bisa menjadi frontline communicators dalam sistem kebencanaan yang berbasis komunitas.
Dengan demikian, bencana tidak hanya menguji ketahanan alam, tetapi juga menantang cara kita berkolaborasi.
Setiap kali air meluap atau api membakar lahan, yang diuji bukan hanya tanggul dan pompa air, tetapi seberapa kuat hubungan antara pemerintah, warga, dan pengetahuan lokal.
Kepercayaan publik tidak tumbuh dari arahan satu arah, melainkan dari ruang partisipasi yang nyata.
Tata kelola bencana masa depan perlu beralih dari pendekatan reaktif menuju model kolaboratif dan ko-kreasi kebijakan (collaborative and co-creation governance).
Pemerintah tidak cukup hanya mengundang warga untuk mendengar, tetapi membuka ruang agar warga ikut merancang solusi.
Pendekatan ini selaras dengan literatur co-creation kontemporer (Voorberg et al., 2015; Osborne et al., 2021) yang menekankan bahwa kebijakan yang efektif lahir dari proses bersama, bukan sekadar produk pemerintah.
Melalui kolaborasi semacam itu, komunikasi tidak lagi sekadar urusan menyampaikan pesan, melainkan cara membangun kesepahaman sosial di tengah krisis.
Pada akhirnya, bencana tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa diperkecil jika komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi tumbuh seiring.
Karena di antara sirene peringatan dini dan laporan cuaca, yang paling menentukan tetaplah suara manusia yang mau mendengar dan bergerak bersama. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Husni-Thamrin7.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Dr-ahmad-Maulana-Manajemen-Unsri.jpg)




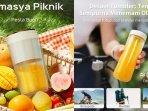


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Rillando-Maranansha.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Husni-Thamrin6.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Amidi-SE-Dosen-UMP.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Isni-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/thamrin-pengamat.jpg)


:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Amidi-SE-Dosen-UMP.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Isni-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/thamrin-pengamat.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Uswatun-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Mohammad-Adi-Putra.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.