Opini
Komunikasi Kebencanaan: Titik Buta Tata Kelola di Indonesia
Banyak pesan kebencanaan disusun dalam bahasa teknokratik yang sulit dipahami, padahal dalam situasi darurat, setiap detik dan setiap kata berarti.
Dalam tata kelola bencana, komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bagian dari proses pemerintahan itu sendiri.
Dalam konteks ini, istilah komunikasi kebencanaan—yang dalam literatur internasional disebut crisis and emergency risk communication (CERC)—merujuk pada pertukaran informasi yang cepat, jelas, dan empatik antara pemerintah, ahli, dan masyarakat untuk melindungi keselamatan publik (WHO, 2018; UNDRR, 2022).
Dengan demikian, komunikasi kebencanaan tidak boleh dipahami sempit sebagai strategi citra lembaga, tetapi sebagai mekanisme penyelamatan.
Namun di Indonesia, ia masih sering dipahami sempit sebagai urusan konferensi pers, bukan sistem informasi publik yang menyelamatkan nyawa.
Jika dicermati, akar persoalannya bukan hanya keterlambatan informasi, melainkan kurangnya empati dan kejelasan dalam komunikasi publik pemerintah.
Banyak pesan kebencanaan disusun dalam bahasa teknokratik yang sulit dipahami warga, padahal dalam situasi darurat, setiap detik dan setiap kata berarti.
Dalam collaborative governance (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015), tata kelola yang baik dibangun di atas kepercayaan dan kapasitas bersama.
Prinsip yang sama berlaku dalam komunikasi kebencanaan. Selama hubungan antarinstansi dibangun atas dasar formalitas, bukan kepercayaan, koordinasi akan tetap terjebak dalam birokrasi lambat.
Paradigma baru Komunikasi Kebencanaan
Kita membutuhkan paradigma baru: komunikasi sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar alat bantu kebijakan.
Informasi tentang risiko, peringatan, dan tindakan harus menjadi hak publik, bukan milik lembaga.
Langkah konkret dapat dimulai dari:
- Membangun platform komunikasi risiko terpadu di setiap provinsi yang menggabungkan data dari BMKG, BPBD, dan KLHK;
- Memperkuat kapasitas juru bicara daerah agar cepat, jelas, dan dipercaya;
- Melibatkan universitas serta media lokal sebagai mitra pengetahuan; dan
- Memperkuat jaringan partisipatif seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk di berbagai wilayah rawan karhutla.
Selama ini, MPA berperan penting dalam pencegahan dan pemadaman dini (KLHK, 2024).
Namun peran mereka dapat diperluas: tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menjadi simpul komunikasi publik — menyampaikan peringatan dini, melaporkan kondisi lapangan, dan menjembatani warga dengan pemerintah.
Dengan pelatihan komunikasi risiko yang memadai, MPA bisa menjadi frontline communicators dalam sistem kebencanaan yang berbasis komunitas.
Dengan demikian, bencana tidak hanya menguji ketahanan alam, tetapi juga menantang cara kita berkolaborasi.
Setiap kali air meluap atau api membakar lahan, yang diuji bukan hanya tanggul dan pompa air, tetapi seberapa kuat hubungan antara pemerintah, warga, dan pengetahuan lokal.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Husni-Thamrin7.jpg)



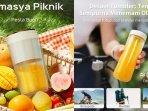















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.